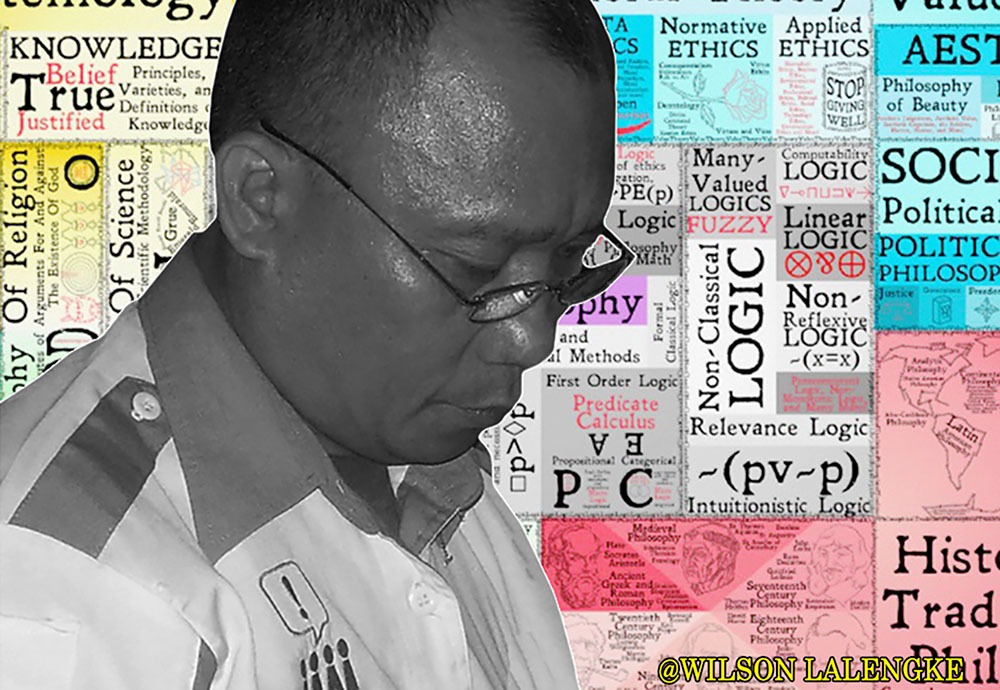_Oleh: Wilson Lalengke_
Jakarta – _Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton, 1887)._ Terjemahan bebas kira-kira begini: Kekuasaan hampir pasti melahirkan korupsi dan kekuasaan mutlak pasti memperanakkan korupsi secara mutlak. Ungkapan itu merupakan bagian dari tulisan Bangsawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg-Acton, kepada Uskup Creighton dalam suratnya yang membahas masalah moral dalam proses peradilan. Acton menekankan keharusan penerapan standar moral yang sama kepada semua orang, tidak terkecuali terhadap tokoh politik dan pemimpin agama.
Adagium Acton tersebut telah menjadi rujukan bagi banyak negara dalam membangun prinsip-prinsip negara domokrasi yang membatasi kekuasaan, baik kekuasaan pemerintahan, kekuasaan bisnis, maupun lembaga dan organisasi non pemerintahan lainnya. Pembatasan-pembatasan yang diterapkan melalui pembuatan undang-undang itu bertujuan agar setiap orang atau kelompok orang tidak menggungakan kekuasaan yang dipegangnya secara sewenang-wenang, yang akan menggiring seseorang menggunakan kekuasaan tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu pada hakekatnya ditujukan untuk menghindarkan diri para pemegang kekuasaan dari perilaku koruptif.
Berdasarkan daftar penilaian korupsi negara-negara di dunia yang diterbitkan oleh Global Transparency International tahun 2023, Indonesia menduduki posisi ke-115 dari 180 negara dengan score 34. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Singapore dan Vietnam. Bahkan, negara bekas provinsi ke-27 Republik Indonesia, Timor Leste, justru bertengger di posisi yang jauh lebih baik, yakni rangking ke-77.
Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Perilaku koruptif di kalangan bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Konon di zaman Kerajaan Majapahit, setiap pelaku korupsi akan dihukum berat. Dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca disebutkan bahwa orang yang mengurangi penghasilan (gaji) atau makanan pekerja, atau mengkorupsi dengan cara mempersempit sawah orang lain, orang tersebut dianggap sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati. Hukuman mati biasanya berupa dipenggal kepala, dibakar hidup-hidup, hukum gantung, atau diseret oleh gajah.
Suatu waktu di awal tahun 1970-an, seorang camat berkunjung ke desa saya di wilayah Morowali Utara. Dari koridor rumah bambu kami, saya yang masih kanak-kanak memandangi sang camat lewat di jalan depan rumah. Dia terlihat agak sempoyongan dengan perut buncitnya yang mirip ibu hamil 9 bulan. Saya bertanya kepada nenek mengapa si camat yang adalah seorang lelaki perutnya gendut persis seperti ibu hamil? Saya tidak pernah melihat lelaki demikian sebelumnya. Nenek menjawab serius, si camat makan uang rakyat sehingga perutnya membesar. Saya mengangguk seakan mengerti. Padahal sesungguhnya yang saya pahami atas jawaban nenek adalah bahwa di dalam perut si camat banyak uang koin (benggol) yang terbuat dari perak atau kuningan yang ditelannya dan tidak bisa dikeluarkan lagi.
Korupsi sudah menjadi diksi umum yang terucapkan di setiap percakapan warga. Mulai dari tingkatan elit istana hingga di level diskusi warga di warung-warung kopi perkampungan kumuh. Melakukan korupsi terkesan telah menjadi hal biasa. Di beberapa kalangan, korupsi dengan segala bentuk dan variannya justru telah menjadi budaya dan dibanggakan. Korupsi bukan lagi sebuah perilaku aneh, ganjil, apalagi ditabukan. Korupsi adalah pelumas pembangunan, kata seorang politisi senior di DPR RI. Korupsi sedikit-sedikit tidak apa-apa, timpal Menteri senior di Istana Negara.
Kini, korupsi tidak hanya dilakukan para pemegang kekuasaan pemerintahan yang notabene merupakan pengelola keuangan negara. Korupsi sudah merambah kemana-mana. Perilaku koruptif uang rakyat sudah menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pengemban amanah kerohanian, plus ormas-ormas dan partai politik. Sejak penerapan Undang-Undang Desa, kucuran triliunan dana desa telah menjadi sasaran empuk kepala desa di hampir seluruh desa di negeri ini untuk dikorupsi.
Teranyar, mencuat kasus korupsi di kalangan wartawan. Tersebutlah pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terseret dalam pusaran perkara korupsi dan penggelapan dana hibah yang digelontorkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka yang terlibat antara lain Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun; Sekretaris Jenderal, Sayid Iskandayah; Wakil Bendahara Umum, Muhammad Ihsan; dan Direktur UMKM, Syarif Hidayatullah. Dalam kasus ini, pengurus Dewan Pers diduga kuat terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Kejadian ini sesungguhnya hanyalah titik puncak ‘nasib sial’ dari rangkaian perilaku korupsi yang sudah membudaya cukup lama secara masif, terstruktur, dan sistematis, di kalangan wartawan dari organisasi pers tertua di Indonesia itu.
Kalangan sosiolog meyakini bahwa konten media atau berita dan informasi yang ditayangkan di media-media bukanlah sesuatu yang benar-benar realitas objektif, tetapi hanya mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai mereka yang berkuasa di suatu komunitas atau bangsa. Oleh sebab itu, ketika para wartawan telah berselingkuh dengan para penguasa, sebagaimana dalam kasus PWI – Kementerian BUMN, maka dapat dipastikan korupsi tumbuh seperti jamur di musim hujan.
Faktanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak lebih dari 20 tahun lalu, namun korupsi tidak kunjung berakhir. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, korupsi semakin meraja-lela. Ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi terus berkembang pesat, baik dari sisi jumlah pelaku maupun kualitas modus operandi serta nominal dana yang dikorupsi.
Ajaibnya, korupsi juga tumbuh subur di lingkungan lembaga anti rasuah bernama KPK itu. Korupsi dilakukan oleh hampir semua personil, mulai dari pimpinan puncak hingga ke staf penjaga sel tahanan KPK. Nominal bervariasi, namun angkanya bikin kita bergidik geleng kepala. Dengan kondisi ini, bagaimana mungkin korupsi dapat dihilangkan, atau minimal berkurang, tatkala lembaga ad-hock yang diharapkan memberantas korupsi justru terseret arus ikut melakukan korupsi?
Pertanyaan seriusnya adalah mengapa gerombolan manusia di kedua lembaga itu, PWI dan KPK, dapat terjerembab dengan mudah ke kubangan korupsi? Kata Ebiet, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Tapi, tidak sesederhana itu Kang Ebiet. Sebab ketika pagar-pagar memegang kekuasaan, niscaya mereka menjelma jadi pemangsa tanaman yang dijaganya. Dan rumputpun diam tak mampu menjawab sekatapun. Tersebab moralitas hilang dari badan oleh kekuasaan ( _power_ ), jangankan hartanya, tinja temannya pun akan mereka tilap hingga tandas. Itulah kondisi darurat korupsi terparah yang siap hancurkan negeri ini berkeping-keping sebentar lagi. (*)
_Penulis adalah jurnalis warga anti korupsi garis keras_